REVAN FAUZI HANDHIKA_2510831030
Ilmu politik universitas andalas
Media Bangsa – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur bukanlah sekadar proyek pembangunan fisik. Ia adalah proyek politik, ekonomi, sekaligus peradaban yang digadang-gadang mampu mengubah wajah Indonesia di abad ke-21. Pemerintah menyebut IKN Nusantara sebagai simbol transformasi menuju pemerataan pembangunan, pusat inovasi hijau, dan penanda era baru demokrasi Indonesia.
Namun, di balik narasi optimistis itu, bayang-bayang politik terus menghantui. Tahun 2028 diproyeksikan sebagai momen ketika IKN bukan lagi sekadar kota pemerintahan, melainkan juga kota politik—pusat kekuasaan yang sarat kepentingan elit. Di sinilah tantangan kritisnya: apakah IKN benar-benar menjadi lokomotif transformasi, atau justru menjelma menjadi panggung politik baru yang jauh dari janji awal?
Narasi Transformasi: Janji Pemerataan dan Modernisasi
Sejak awal, gagasan pemindahan ibu kota didorong oleh dua alasan utama: ketimpangan pembangunan Jawa–luar Jawa dan beban berat Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, sekaligus populasi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa IKN bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan, tetapi juga “simbol transformasi menuju Indonesia maju.”
Dalam teori politik pembangunan, pemindahan pusat negara kerap dianggap sebagai strategi redistribusi kekuasaan dan ekonomi. Harold Crouch, misalnya, menyatakan bahwa “kebijakan publik di negara berkembang sering kali lebih simbolis ketimbang substansial, tetapi simbol itu bisa menjadi instrumen mobilisasi kekuatan politik.” Dengan kata lain, IKN adalah simbol sekaligus strategi.
Dari sudut pandang mahasiswa ilmu politik, kita bisa membaca ini sebagai upaya pemerintah menciptakan nation branding: memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang visioner, siap menyongsong era baru dengan kota modern dan hijau. Tentu, secara konsep ini patut diapresiasi.
Bayang-Bayang Politik: Dari Kota Hijau ke Kota Kekuasaan
Meski narasinya optimis, realitas politik tak bisa diabaikan. Proyeksi 2028 memperlihatkan bahwa IKN bukan hanya kota pemerintahan, tetapi juga akan menjadi episentrum politik baru. Partai-partai besar mulai membidik IKN sebagai panggung konsolidasi kekuasaan. Elit-elit politik mulai melirik lahan, proyek, dan jaringan ekonomi yang akan tumbuh di sekitarnya.
Inilah paradoks besar IKN: dari semangat pemerataan, ia bisa berubah menjadi arena perebutan rente. Michel Foucault pernah menegaskan, “kekuasaan tidak pernah netral; ia selalu beroperasi melalui ruang, institusi, dan relasi sosial.” IKN adalah ruang baru itu. Jika dikelola dengan logika oligarki, maka ia hanya akan memperpanjang dominasi elit, bukan membuka ruang bagi rakyat.
Demokrasi Liberal dan Politik Infrastruktur
Kita hidup di era demokrasi liberal, di mana kekuasaan politik sering kali dijalankan melalui logika pasar. Infrastruktur menjadi komoditas politik. Proyek besar seperti IKN, meski diklaim sebagai kepentingan nasional, tetap sarat dengan kepentingan ekonomi dan elit tertentu.
Sebagai mahasiswa politik, kita harus kritis melihat fenomena ini. Pemindahan ibu kota tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan: siapa yang diuntungkan? Apakah benar rakyat kecil di Kalimantan akan menikmati manfaatnya, ataukah hanya segelintir pengusaha dan politisi?
Samuel P. Huntington menulis, “institusi politik yang stabil adalah mereka yang mampu menjawab tuntutan masyarakat tanpa terjebak pada kepentingan segelintir elit.” Pertanyaan besarnya, apakah IKN akan menjelma sebagai institusi politik baru yang stabil dan inklusif, ataukah sekadar arena politik transaksional?
Harapan Transformasi yang Belum Padam
Meski kritiknya tajam, kita tidak bisa menutup mata bahwa IKN tetap menyimpan potensi besar. Jika dikelola dengan paradigma pembangunan yang partisipatif, transparan, dan inklusif, IKN bisa menjadi tonggak baru demokrasi Indonesia. Kota ini bisa dirancang sebagai ruang politik yang sehat, di mana transparansi, partisipasi warga, dan teknologi digital mendorong keterbukaan.
IKN juga berpotensi memutus rantai Jawa-sentrisme yang sudah mengakar lama. Dengan memindahkan pusat politik ke Kalimantan, Indonesia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berputar di Pulau Jawa. Ini bisa menjadi revolusi struktural jika dikelola dengan serius.
Namun, syaratnya jelas: pemerintah harus berani menghadapi dominasi oligarki, memastikan tata kelola yang bersih, dan menjamin keterlibatan masyarakat lokal. Tanpa itu, IKN hanya akan jadi “Jakarta kedua” dengan wajah berbeda tetapi problem serupa.
Posisi Mahasiswa: Antara Optimisme dan Kewaspadaan
Sebagai mahasiswa ilmu politik, kita berada pada posisi unik: bukan sekadar pengamat pasif, tetapi juga agen kritis yang bisa mengawal arah pembangunan politik bangsa. Sikap kita terhadap IKN seharusnya bukan sekadar mendukung atau menolak, melainkan mengawal.
Optimisme boleh ada, karena IKN menyimpan peluang transformasi. Tetapi kewaspadaan harus lebih besar, karena sejarah pembangunan di negeri ini sering dikooptasi oleh elit dan oligarki. Jalanan mungkin bukan lagi satu-satunya arena perjuangan mahasiswa, tetapi ruang akademik, digital, dan masyarakat sipil tetap harus menjadi panggung kita untuk menggugat jika IKN keluar jalur.
Penutup
IKN 2028 adalah persimpangan sejarah. Ia bisa menjadi simbol revolusi struktural yang memutus rantai ketimpangan, atau justru menjadi kota politik yang memperpanjang kekuasaan oligarki.
Harapan transformasi tetap ada, tetapi bayang-bayang politik tidak bisa diabaikan. Tugas mahasiswa adalah menjaga agar IKN tidak sekadar jadi panggung elit, melainkan benar-benar ruang demokrasi baru bagi rakyat Indonesia.
Seperti kata Gramsci, “pesimisme intelek harus disertai optimisme kehendak.” Dengan intelek, kita kritis melihat bahaya oligarki di balik IKN. Dengan kehendak, kita optimis bahwa perubahan tetap mungkin terjadi—selama rakyat dan mahasiswa tidak melepaskan perannya.
Daftar Pustaka
Crouch, Harold. Political Reform in Indonesia after Soeharto. Singapore: ISEAS, 2010.
Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995.
Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.
Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.




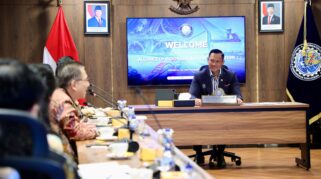


Tinggalkan Balasan